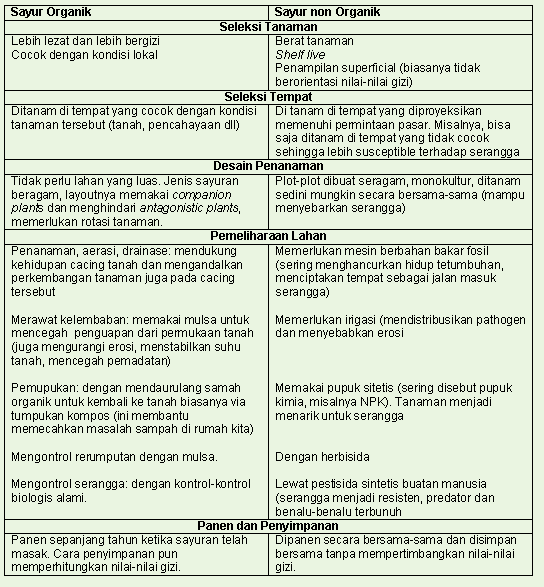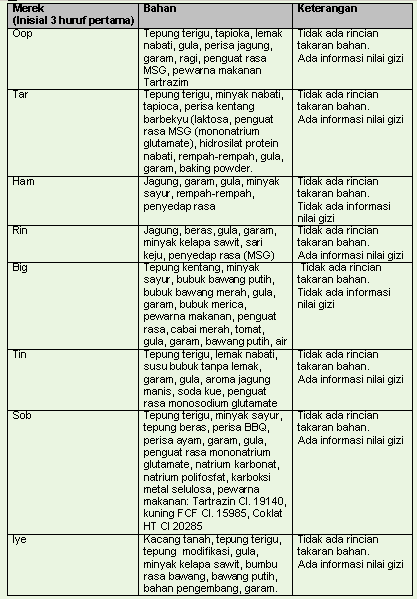Belum lama ini aku cuti dan singgah di rumah kawan suamiku di Desa Sumberjati, Kademangan, Blitar. Wilayah berkapur itu sungguh sejuk. Tuan rumah adalah petani, sekaligus peternak.
Di desa itu aku sempat merasakan buang air besar di jumbleng, istilahnya orang Jawa. Tuan rumah tidak memiliki WC. Jumbleng itu lubang tempat buang air besar di kebun. Letaknya relatif jauh karena aku diantar tuan rumah melewati dua rumah dengan jarak yang relatif berjauhan satu sama lain. Jumbleng itu ada di kebun yang sangat luas.
Tempat itu kecil saja. Sekelilingnya ditutupi batu-bata yang sudah lumutan. Di dalamnya, kita menginjak tegel semen. Cuma tersisa lubang sebesar satu bata untuk kotoran. Aku ngepas-paskan agar kotoranku bisa masuk lubang. Cukup khawatir juga. Untung tinja itu sukses masuk lubang.
Saat ada di "toilet" itu, aku tidak membaui tinja. Padahal isinya jelas tinja. Apa karena ada di kebun terbuka atau karena di daerah yang tanahnya berkapur? Entahlah. Tapi aku ingat waktu kecil pernah pula pergi ke Mojokerto dan buang air di jumbleng. Baunya, sampai sekarang masih kukenang.
Aku berpikir-pikir, apa yang membuatnya tidak berbau sedangkan jumbleng serupa di kebun di sebuah desa di Mojokerto berbau. Aku melihat sekelilingku. Mungkinkah karena di sekitar jumbleng banyak pohon? Di antara berbagai macam pohon yang menyejukkan dan membawa damai di hati ini, aku hanya kenal beberapa. Selebihnya tidak. Apakah mungkin salah satu atau beberapa pohon ini yang menetralkan bau tak sedap? Aku langsung ingat kompleks pekuburan di Trunyan, Bali, tempat mayat-mayat digeletakkan begitu saja. Mayat-mayat di pekuburan ini tidak berbau busuk karena di sekitarnya terdapat pohon yang bisa menetralkan bau tidak sedap. Mungkinkah di pekarangan tempat aku buang air besar itu ada pohon sebagaimana yang ada di Trunyan? Mungkinkah ada treatment khusus dengan cara organik yang membuat juglangan tersebut ter-manage sehingga tidak pernah meledak meskipun lubangnya kecil?
Hasrat untuk bertanya-tanya soal jumbleng dan nasib tinja di dalamnya ini sesungguhnya begitu kuat dalam diriku. Namun untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada si tuan rumah aku sungkan. Soalnya, kulihat, tuan rumahku juga sungkan karena aku harus pakai juglangan itu. Beberapa kali dia minta maaf soal ini padaku. Padahal aku nggak masalah. Malah bersyukur bisa mengalami sesuatu di luar kebiasaan. Pengalaman berharga seperti ini jarang kudapatkan.
Oh ya, aku kepikiran tentang jumbleng tersebut sampai sekarang. Aku agak menyesal sebenarnya, kenapa itu nggak kupotret padahal aku membawa kamera. Tinja yang ada di dalam jumbleng yang masih banyak di desa itu, sesungguhnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, sebagaimana yang dilakukan kantorku. Dengan sedikit instalasi, pupuk-pupuk yang berasal dari tinja bisa dipanen untuk sawah mereka. Di desa itu banyak terdapat sawah. Sayangnya, dari hasil obrolan dengan tuan rumah, mereka masih memakai metode konvensional untuk mengolah lahan. Mereka tidak bercocok tanam dengan cara-cara organik. Padahal yang organik di samping menyehatkan juga sangat irit dan arif terhadap lingkungan. Tuan rumah sesungguhnya tahu itu, namun dia bilang belum melakukan cocok tanam organik karena semua keperluan sawah adalah hasil drop-dropan.
Tempat itu kecil saja. Sekelilingnya ditutupi batu-bata yang sudah lumutan. Di dalamnya, kita menginjak tegel semen. Cuma tersisa lubang sebesar satu bata untuk kotoran. Aku ngepas-paskan agar kotoranku bisa masuk lubang. Cukup khawatir juga. Untung tinja itu sukses masuk lubang.
Saat ada di "toilet" itu, aku tidak membaui tinja. Padahal isinya jelas tinja. Apa karena ada di kebun terbuka atau karena di daerah yang tanahnya berkapur? Entahlah. Tapi aku ingat waktu kecil pernah pula pergi ke Mojokerto dan buang air di jumbleng. Baunya, sampai sekarang masih kukenang.
Aku berpikir-pikir, apa yang membuatnya tidak berbau sedangkan jumbleng serupa di kebun di sebuah desa di Mojokerto berbau. Aku melihat sekelilingku. Mungkinkah karena di sekitar jumbleng banyak pohon? Di antara berbagai macam pohon yang menyejukkan dan membawa damai di hati ini, aku hanya kenal beberapa. Selebihnya tidak. Apakah mungkin salah satu atau beberapa pohon ini yang menetralkan bau tak sedap? Aku langsung ingat kompleks pekuburan di Trunyan, Bali, tempat mayat-mayat digeletakkan begitu saja. Mayat-mayat di pekuburan ini tidak berbau busuk karena di sekitarnya terdapat pohon yang bisa menetralkan bau tidak sedap. Mungkinkah di pekarangan tempat aku buang air besar itu ada pohon sebagaimana yang ada di Trunyan? Mungkinkah ada treatment khusus dengan cara organik yang membuat juglangan tersebut ter-manage sehingga tidak pernah meledak meskipun lubangnya kecil?
Hasrat untuk bertanya-tanya soal jumbleng dan nasib tinja di dalamnya ini sesungguhnya begitu kuat dalam diriku. Namun untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada si tuan rumah aku sungkan. Soalnya, kulihat, tuan rumahku juga sungkan karena aku harus pakai juglangan itu. Beberapa kali dia minta maaf soal ini padaku. Padahal aku nggak masalah. Malah bersyukur bisa mengalami sesuatu di luar kebiasaan. Pengalaman berharga seperti ini jarang kudapatkan.
Oh ya, aku kepikiran tentang jumbleng tersebut sampai sekarang. Aku agak menyesal sebenarnya, kenapa itu nggak kupotret padahal aku membawa kamera. Tinja yang ada di dalam jumbleng yang masih banyak di desa itu, sesungguhnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, sebagaimana yang dilakukan kantorku. Dengan sedikit instalasi, pupuk-pupuk yang berasal dari tinja bisa dipanen untuk sawah mereka. Di desa itu banyak terdapat sawah. Sayangnya, dari hasil obrolan dengan tuan rumah, mereka masih memakai metode konvensional untuk mengolah lahan. Mereka tidak bercocok tanam dengan cara-cara organik. Padahal yang organik di samping menyehatkan juga sangat irit dan arif terhadap lingkungan. Tuan rumah sesungguhnya tahu itu, namun dia bilang belum melakukan cocok tanam organik karena semua keperluan sawah adalah hasil drop-dropan.
Tinja manusia, di samping kotoran hewan, menurutku merupakan salah satu solusi kelangkaan pupuk yang kini benar-benar membawa petani di jurang kehancuran. Aku sesungguhnya ingin ngobrol lebih dalam tentang hal ini dengan tuan rumah. Aku juga pengen mendapat ilmu pertanian darinya karena separo hidupnya didedikasikan pada pertanian. Pastilah ia sangat ahli dan bisa membagikan ilmunya padaku. Sebaliknya, aku, mungkin bisa membagikan sedikit pengetahuanku tentang pupuk urine dan tinja manusia.
Sesungguhnya, alam telah menyediakan segalanya untuk semua makhluk ciptaan-Nya. Tinja pun bisa jadi berkah asal tahu pengelolaan dan pemanfaatannya. Kantorku, Pusdakota, telah mempraktikkan pengolahan urine dan tinja manusia dan hasilnya dipakai untuk menyuburkan tanah di kebun Pusdakota. Untuk tanah-tanah di desa yang subur, sebetulnya nggak perlu khawatir tentang organisme yang merugikan kesehatan, yang dibawa tinja ataupun urine. Memang ada sih, macam E-Coli. Tapi, bila bersentuhan dengan tanah subur, mereka kemungkinan besar nggak bisa hidup lama. Asal dikelola dengan baik, pasti oke.
Dari yang aku pernah baca, pemanfaatan tinja manusia sesungguhnya sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Tapi manusia kini sudah melupakannya. Sebagaimana kini, para petani di desa seringkali tidak tahu cara membuat kompos dari kotoran hewan maupun daun-daunan. Padahal itu warisan nenek moyang. Kini, sistem telah membuat petani terpaksa membeli pupuk sintetis atau kimia yang merusak tanah maupun ekosistem.
Sesungguhnya, alam telah menyediakan segalanya untuk semua makhluk ciptaan-Nya. Tinja pun bisa jadi berkah asal tahu pengelolaan dan pemanfaatannya. Kantorku, Pusdakota, telah mempraktikkan pengolahan urine dan tinja manusia dan hasilnya dipakai untuk menyuburkan tanah di kebun Pusdakota. Untuk tanah-tanah di desa yang subur, sebetulnya nggak perlu khawatir tentang organisme yang merugikan kesehatan, yang dibawa tinja ataupun urine. Memang ada sih, macam E-Coli. Tapi, bila bersentuhan dengan tanah subur, mereka kemungkinan besar nggak bisa hidup lama. Asal dikelola dengan baik, pasti oke.
Dari yang aku pernah baca, pemanfaatan tinja manusia sesungguhnya sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Tapi manusia kini sudah melupakannya. Sebagaimana kini, para petani di desa seringkali tidak tahu cara membuat kompos dari kotoran hewan maupun daun-daunan. Padahal itu warisan nenek moyang. Kini, sistem telah membuat petani terpaksa membeli pupuk sintetis atau kimia yang merusak tanah maupun ekosistem.
Kadang aku heran. Kantorku Pusdakota kebanjiran permintaan dari para petani untuk diajari membuat pupuk. Kami memfasilitasi banyak training pertanian organik untuk wilayah pedesaan. Lo, kita di kota menularkan ilmu pertanian dan pembuatan pupuk untuk orang desa? Kayaknya dunia sudah kebalik. Tapi begitulah faktanya. Berbekal model close system budidaya yang telah kami kembangkan, baik di Surabaya maupun Blitar, permintaan training datang dari berbagai desa.
Padahal kami, staf Pusdakota, justru lebih banyak belajar dari para sesepuh desa-desa mana pun yang masih ingat tentang bagaimana membuat kompos. Kami belajar dari praktisi-praktisi pertanian organik yang mau berbagi ilmu. Apa yang kami dengar, kami rekam, praktikkan dan kami uji terus-menerus. Itu yang kemudian kami tularkan lagi ke saudara-saudara kami, petani di desa. Tidak saja secara teknis kami berbagi tentang pertanian organik, tapi juga soal spirit karena justru ini yang harus menjadi perhatian utama. (Alpha Savitri)